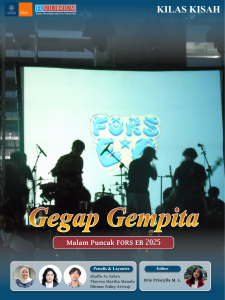Penulis: Anonim/EQ
Editor: Anonim/EQ
Layouter: Anonim/EQ
Perluasan Peran TNI dalam Ranah Sipil
Pada 20 Maret 2025, dalam Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya melalui pimpinan sidang, Puan Maharani. Salah satu poin yang memicu polemik adalah perluasan tugas dan wewenang TNI dalam urusan sipil yang dikhawatirkan membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (2025) menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi menguatkan impunitas anggota TNI, khususnya dalam kasus hukum yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan (KtP). Revisi ini memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki posisi strategis di Mahkamah Agung dan lembaga yudisial lainnya. Hal ini berisiko melemahkan supremasi sipil dalam peradilan, serta mengancam prinsip independensi kekuasaan yudisialsebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
LBH APIK (2025) mengingatkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas peradilan, yang menjadi bagian penting dari akses keadilan bagi perempuan menurut Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women. Berdasarkan pengalaman mereka dalam mendampingi korban, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya diproses di pengadilan umum justru dialihkan ke peradilan militer. Akibatnya, korban kesulitan mengakses keadilan karena sistem peradilan militer belum menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 yang menjamin penanganan perkara yang responsif bagi perempuan.
Kekhawatiran itu sejalan dengan laporan Komnas yang mencatat sedikitnya 190 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Meskipun tergolong sebagai tindak pidana umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seluruh kasus tersebut tetap ditangani melalui mekanisme peradilan militer. Padahal, hukum umum dan hukum militer memiliki perbedaan signifikan, baik dari segi pedoman hukum yang digunakan, kewenangan lembaga yang mengadilinya, maupun tahapan proses peradilannya. Proses hukum ini kerap dikeluhkan oleh korban dan pendampingnya karena berbagai hambatan, baik dalam hal substantif, struktural, maupun kultural. Hambatan-hambatan tersebut menyulitkan mereka memperoleh akses informasi, penanganan kasus yang adil, serta proses yang mengarah pada pemulihan korban (Komnas Perempuan, 2025).
Maskulinitas dalam Tubuh Militer
Dalam masyarakat patriarkal, terdapat hierarki maskulinitas yang ditentukan berdasarkan sejauh mana masing-masing bentuk maskulinitas mendukung dan merepresentasikan nilai-nilai patriarki. Bentuk maskulinitas yang paling diakui dan dilegitimasi inilah yang disebut sebagai maskulinitas hegemonik. Connell dalam Choo (2020) menyatakan bahwa maskulinitas hegemonik merupakan praktik sosial yang membentuk norma gender dominan yang mendukung legitimasi patriarki. Bentuk ini memastikan posisi laki-laki tetap dominan, sementara perempuan tetap berada dalam posisi subordinat dalam struktur sosial yang ada.
Pengesahan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait perluasan tugas dan wewenang militer di ranah sipil menimbulkan kekhawatiran yang tidak bisa dilepaskan dari konteks perjuangan gerakan perempuan. Keterlibatan militer dalam urusan sipil secara historis telah berdampak pada penyempitan ruang sipil, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam posisi marjinal, termasuk perempuan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada 18 Maret 2025, Aliansi Perempuan Indonesia menyuarakan keprihatinan atas revisi tersebut dan menilai bahwa ekspansi peran militer berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat, terutama bagi mereka yang paling rentan (Rifaldy Zenal, 2025).
Data terbaru menunjukkan bahwa partisipasi prajurit perempuan masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 10 hingga 15 persen dari total keseluruhan pasukan militer. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan budaya yang membuat perempuan sulit untuk berperan lebih signifikan dalam militer, Target internal TNI untuk keterwakilan perempuan sekitar 30 persen, tetapi kenyataannya yang telah dicapai masih jauh dari angka tersebut (Mabes, 2024). Walaupun perempuan telah bekerja di lingkungan militer, perbedaan gender masih tampak, terutama dalam pembagian tugas. Perempuan umumnya hanya diberi kesempatan menangani urusan yang berkaitan dengan administrasi dan logistik (Safitri & Listyani, 2021). Hal ini secara tidak langsung membatasi akses mereka pada pengalaman di bidang tempur atau komando, memperkuat kesenjangan karier, dan menghambat peluang perempuan untuk menembus posisi strategis di tubuh militer. Rendahnya partisipasi perempuan di militer tidak hanya mencerminkan ketimpangan internal dalam institusi pertahanan, tetapi juga menjadi indikator kuat atas budaya organisasi yang cenderung maskulin dan patriarkal. Perluasan peran militer ke ranah sipil berisiko menyebarkan budaya militer yang maskulin ke institusi sipil. Ketika institusi dengan karakteristik seperti ini diperluas ke ranah sipil, maka nilai-nilai dan struktur kekuasaan yang serupa sangat mungkin ikut terbawa masuk.
Jejak Sejarah Militerisme terhadap Perempuan
Dalam sejarah politik Indonesia, keterlibatan militer dalam urusan sipil sudah pernah terjadi melalui konsep dwifungsi ABRI yang mulai diterapkan secara resmi pada masa Orde Baru. Dwifungsi ABRI merupakan sebuah doktrin dalam tubuh militer Indonesia yang menyatakan bahwa ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara, tetapi juga berperan dalam mengelola kekuasaan serta menjalankan fungsi pemerintahan (Suryawan dan Sumarjiana, 2020). Konsep ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang serius karena membuka ruang dominasi militer di ranah sipil, mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dalam Faturahman (2025) menilai bahwa penempatan prajurit TNI di jabatan sipil tidak hanya berisiko mengikis prinsip supremasi sipil, tetapi juga merusak sistem merit dan profesionalisme aparatur negara.
Keberadaan militer di ruang sipil ikut melanggengkan batasan-batasan terhadap perempuan. Salah satu bentuknya yang paling jelas adalah domestikasi perempuan yang terjadi selama masa Orde Baru. Julia Suryakusuma (2011), dalam bukunya, Ibuisme Negara, menjelaskan bagaimana negara dengan bantuan militer mendorong perempuan untuk berperan sebagai ibu dan istri yang patuh, bukan sebagai warga negara yang mandiri ataupun sebagai perempuan yang berdaya. Dalam paham ibuisme ini, perempuan diharapkan mengabdi sepenuhnya kepada suami, anak, keluarga, dan negara.
Meskipun rezim Orde Baru telah berakhir, warisan ideologinya masih terus hidup dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik Indonesia, termasuk dalam cara negara memandang dan mengatur peran perempuan. Kabullah & Fajri (2019) dalam studinya, Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019, menunjukkan bahwa meskipun perempuan diizinkan tampil di ruang publik, bahkan ikut serta dalam pemilihan umum, keterlibatan mereka sering kali tetap dibatasi oleh peran tradisional sebagai istri dan ibu. Pola yang memberi ruang bagi perempuan untuk tampil di publik namun tetap menekankan peran domestiknya adalah ciri khas dari apa yang kini disebut sebagai neo-ibuism dalam konteks politik pasca-Orde Baru.
Fajri (2019) juga menambahkan tentang budaya ”ikut suami” tercermin dalam organisasi-organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita yang telah didirikan sejak masa orde baru. Kedua organisasi ini berfungsi bukan sekadar sebagai wadah kegiatan sosial, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menata kehidupan perempuan. Melalui kegiatan yang berfokus pada urusan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga, perempuan dibimbing atau lebih tepatnya ‘dijinakkan’ agar tetap berada dalam ranah domestik supaya dapat menjadi ‘pendamping suami atau ibu’yang baik. Orde Baru telah tumbang, tetapi belenggu perempuan terus berkembang.
Pada masa Orde Baru, peran perempuan banyak dibatasi dan diarahkan untuk fokus pada urusan domestik. Namun, tidak sedikit perempuan yang berani melawan dan memperjuangkan haknya, meski menghadapi risiko besar. Marsinah adalah salah satu contoh perempuan pemberani yang berjuang demi keadilan di tengah tekanan tersebut. Marsinah, seorang buruh pabrik PT Catur Putra Surya di Sidoarjo, aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama soal kenaikan upah. Ia terakhir kali terlihat pada Rabu malam, 5 Mei 1993, setelah sebelumnya sempat dipanggil ke Kodim bersama beberapa rekannya.
Dalam bukunya, Supartono (1999) dalam bukunya yang berjudul Marsinah: Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia mencatat bahwa tiga hari setelah Marsinah dipanggil ke Kodim, yakni pada Sabtu 9 Mei 1993, mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk sawah di Desa Jegong, Wilangan, Nganjuk, sekitar 120 km dari tempat terakhir Ia terlihat. Hasil otopsi mengungkap bahwa Marsinah mengalami penyiksaan berat sebelum meninggal. Ia menderita luka tusukan di bagian perut, robeknya selaput dara, serta kerusakan parah pada tulang kelamin bagian depan akibat benda tumpul. Kasus ini sempat diselidiki, tetapi penyelidikan berhenti di tengah jalan dan akhirnya ditutup tanpa kejelasan. Nama Marsinah kini hidup sebagai bisikan perlawanan dari tubuh yang tak lagi bernyawa, tetapi masih menuntut keadilan.
Suara yang Tidak Ingin Dibungkam
Revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer dalam kehidupan sipil tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa yang lebih luas dalam tubuh masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang masih diliputi oleh warisan patriarki dan militerisme, kebijakan semacam ini menyimpan resiko besar terhadap penyempitan ruang partisipasi perempuan, baik secara struktural maupun kultural. Ketika institusi yang dibentuk dalam kerangka maskulinitas hegemonik hadir dalam birokrasi dan institusi sipil, nilai-nilai eksklusif, hierarkis, dan patriarkal yang menyertainya sangat mungkin tereproduksi dalam skala yang lebih luas.
Apa yang terlihat hari ini bukanlah hal yang tidak memiliki akar sejarah. Kita telah menyaksikan bagaimana dwifungsi ABRI menciptakan tumpang tindih kuasa yang mengaburkan batas antara militer dan sipil serta bagaimana doktrin ibuisme menjadi alat untuk mendomestikasi peran perempuan secara sistematis. Meski rezim berganti, nilai-nilai yang menopang praktik tersebut belum sepenuhnya hilang. Neo-ibuisme yang muncul dalam lanskap politik elektoral menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam ruang publik seringkali hanya bersifat simbolik, bukan cerminan dari kuasa yang sejati.
Situasi ini diperparah dengan minimnya akuntabilitas institusional atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap perempuan serta eksklusivitas sistem peradilan militer yang menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan. Ketika kekuasaan militer diperluas tanpa pembacaan kritis terhadap dampaknya bagi kelompok rentan, terutama perempuan, maka negara justru sedang menciptakan ulang lanskap sosial-politik yang timpang. Lanskap tempat suara-suara yang kritis dibungkam, partisipasi dibatasi, dan keadilan hanya menjadi jargon. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi militer dalam kehidupan sipil harus ditimbang tidak hanya dari sisi keamanan atau efisiensi birokrasi, tetapi juga dari keberpihakan pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Jika tidak, kita hanya akan terus bergerak dalam lingkaran yang sama, ketika perempuan masih diposisikan sebagai pelengkap demokrasi, bukan subjek yang setara di dalamnya.
REFERENSI
Aflah , M. N., & Mawaddah, L. R. (2021). Pengaruh Glass Ceiling Terhadap Kepemimpinan Strategis Wanita Dalam Bidang Militer Di Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 4(2). https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i2.10054
Carreiras, H. (2021). Gender and the Military in Western Democracies. Oxford Research Encyclopedia of Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1923
Choo, J. (2020). The Spread of Feminism and the Silence of Gendered Militarism in the Neoliberal Era: Controversy Over Military Conscription Among Members of the Young Generation in South Korea
49(4), 477–500. https://snu.elsevierpure.com/en/publications/the-spread-of-feminism-and-the-silence-of-gendered-militarism-in-
Kabbalah, M. I. (2021). Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 136–155. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103421989069
Komnas Perempuan. (2025, Maret 18). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Revisi UU TNI. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-revisi-uu-tni
perempuanthreads. (2025, Maret 21). Pengesahan RUU TNI 2025: Mematikan Demokrasi dan Hak Perempuan. Perempuanthreads.com. https://perempuanthreads.com/detailpost/pengesahan-ruu-tni-2025-mematikan-demokrasi-dan-hak-perempuan
Pertiwi, S. P. (2024, September 18). Kamus Feminis: Pandangan Feminisme Terhadap Oligarki dan Militerisme Yang Abaikan Kesetaraan. Konde.co. https://www.konde.co/2024/09/kamus-feminis-pandangan-feminisme-terhadap-oligarki-dan-militerisme-yang-abaikan-kesetaraan/
puspen. (2024). Jumlah Prajurit Wanita TNI Belum Ideal. Nasional. https://tni.mil.id/view-4932-jumlah-prajurit-wanita-tni-belum-ideal.html
Pertiwi, S. P. (2025, Maret 19). Kenapa Perempuan Harus Tolak Revisi UU TNI? Ancaman Militerisme dari Perspektif Feminis – Konde.co. Konde.co. https://www.konde.co/2025/03/kenapa-perempuan-harus-tolak-revisi-uu-tni-ancaman-militerisme-dari-perspektif-feminis/
[Rilis Pers] LBH APIK Tolak Revisi UU TNI, Tolak Dwifungsi Militer: Ancaman bagi Demokrasi dan Agenda Kesetaraan Gender di Indonesia – Asosiasi LBH APIK Indonesia. (2024). Lbhapik.or.id. https://lbhapik.or.id/rilis-pers-lbh-apik-tolak-revisi-uu-tni-tolak-dwifungsi-militer-ancaman-bagi-demokrasi-dan-agenda-kesetaraan-gender-di-indonesia/
Safitri, E. (2021, April 22). MAKNA DIRI PEREMPUAN PRAJURIT TNI-AD (Studi Korps Wanita Angkatan Darat“KOWAD” Kodam V Brawijaya). Academia.edu; Prodi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. https://www.academia.edu/92398956/MAKNA_DIRI_PEREMPUAN_PRAJURIT_TNI_AD_Studi_Korps_Wanita_Angkatan_Darat_KOWAD_Kodam_V_Brawijaya_
Supartono, A. (1999). Marsinah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Suryakusuma, J. I. (2011). Ibuisme Negara. Komunitas Bambu.
Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI. Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP), 10(2), 182–191. https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092
Wahyuni, W. (2025, Maret 21). Menelusuri Jejak Dwifungsi ABRI di Indonesia. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-jejak-dwifungsi-abri-di-indonesia-lt67dd2ff0e3c6d/
Yusrial, R. M. (2025, Maret 20). Aliansi Perempuan Indonesia Demo di DPR Tuntut Batalkan UU TNI. Tempo. https://www.tempo.co/politik/aliansi-perempuan-indonesia-demo-di-dpr-tuntut-batalkan-uu-tni-1222023
Zelan, R. (2025, Maret 19). Pelemahan Perempuan dan Kelompok Rentan Apabila RUU TNI Disahkan – Bincang Perempuan. Bincang Perempuan; BP.com. https://bincangperempuan.com/pelemahan-perempuan-dan-kelompok-rentan-apabila-ruu-tni-disahkan/