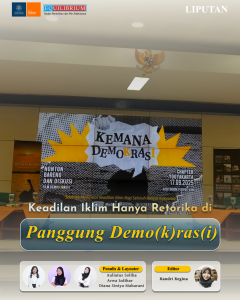Penulis: Kalyca Indira, Dwi Zhafirah, Gigih Candra/EQ
Editor: Aulia Valerie
Layouter: Vidhyazputri Belva/EQ
Yogyakarta—si kota budaya dan pendidikan kini menyimpan wajah lain yang kian mencolok di tengah keramaian, yakni para pengamen yang memenuhi sudut-sudut jalanan. Mereka bukan sekadar pengisi suara latar di lampu merah atau tempat umum, tetapi penanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik geliat kota pelajar ini. Ketimpangan ekonomi dan stagnansi sosial telah mendorong banyak warga, terutama dari masyarakat bawah untuk menjadikan jalanan sebagai satu-satunya panggung bertahan hidup. Fenomena ini bukan semata soal estetika kota atau kenyamanan publik, melainkan cermin dari permasalahan struktural yang lebih dalam. Dilema pun muncul ketika kehadiran mereka dianggap mengganggu, padahal sejatinya mereka adalah korban dari sistem yang tak mampu memberi ruang hidup yang layak.
Pengamen di Mata Masyarakat
Tim penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat mengenai pandangannya terhadap pengamen di Yogyakarta. Menurut narasumber, pengamen di Yogyakarta justru menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Maraknya pengamen juga menunjukkan bahwa masih banyak seniman-seniman yang menguasai Yogyakarta. Akan tetapi, kebanyakan pengamen belum terorganisir dengan baik. Harapan kepada pemerintah agar membuat lembaga khusus bagi pengamen sehingga mereka bisa lebih terstruktur.
Pendapat tersebut berbanding terbalik dengan pandangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menganggap bahwa pengamen di pinggir jalan atau di tempat umum lainnya termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis. Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa kegiatan mengamen itu dilarang, tak terkecuali pengamen yang menggunakan pengeras suara profesional. Pengamen banyak menggunakan badan trotoar untuk menjalankan aktivitas mereka, sehingga dapat mengganggu pejalan kaki (Pandangan Jogja, 2023).
Suara Pengamen
Roby, seorang pengamen yang telah berkarya sejak 2013, menyampaikan pandanganya mengenai perbedaan pengemis dan pengamen. “Menurutku Jogja ini kota seni budaya, kota pelajar juga, jadi kita kan pengamen juga gak asal-asalan. Di sini kita sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), ada aturannya, gak boleh pake sandal jepit, kerapian itu nomor satu. Kita gak rapi aja pada dipandang jelek sama orang karena identitas pengamen. Kita rapi, keren kayak gimana, tetap aja pengamen.” ucap Roby.
Dari pengalaman Roby, ada beberapa temannya yang tidak memiliki KTP ditangkap dan dibina oleh Dinas Sosial Yogyakarta. Pertama kali ditangkap akan dibina selama satu minggu, kedua kali ditangkap akan dibina selama tiga bulan, dan ketiga kali ditangkap bisa dibina selamanya. Namun, beberapa dari mereka ada yang kabur karena rata-rata mereka bukannya “dibina”, melainkan ditahan dan digabung bersama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tanpa diberikan ruang untuk berkarya. Roby menjelaskan bahwa rata-rata orang yang ditangkap itu membangkang, sehingga mereka sering diperlakukan seperti binatang.
Kebijakan dan Realita Sosial Pengamen Jalanan
Di balik dinamika interaksi antara pengamen dan masyarakat, terdapat peran penting pemerintah dalam merespons fenomena sosial ini melalui pembentukan Perda DI Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut yakni pemberian sanksi bagi siapa pun yang memberikan uang kepada pengamen di jalan. Namun, aturan tersebut menuai berbagai pandangan karena masyarakat yang berniat mengapresiasi pengamen atas hiburan yang diberikan justru dikenai sanksi. Lebih lanjut, saat pengamen berupaya meminta solusi kepada pemerintah, respons yang diberikan hanya sekadar memindahkan lokasi aktivitas mereka dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya memindahkan permasalahan tanpa memberikan penyelesaian yang berkelanjutan.
Menurut Dea Yustisia, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), permasalahan pengamen jalanan tidak terlepas dari kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia mengemukakan, “Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi publik sendiri, salah satu masalah mendasarnya adalah mismatch antara regulasi dan realitas sosial. Ketika pengamen dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis dalam Perda, sementara banyak dari mereka sebenarnya memiliki rumah, KTP, dan alat musik yang layak maka terjadi kesenjangan antara definisi hukum dan fakta sosial.”
Menurutnya, praktik “pengamanan” terhadap pengamen masih terlalu homogen tanpa intervensi jangka panjang. Padahal akan ada potensi ekonomi kreatif jika pengamen dikelola dengan benar, seperti diberikan pelatihan kerja ataupun sertifikasi seni jalanan. Tanpa pendekatan yang tepat, permasalahan pengamen jalanan akan terus berlanjut sehingga solusi yang diupayakan sulit tercapai.
Menata Jalanan, Membuka Harapan
Pengamen jalanan bukanlah anomali dalam ruang kota, melainkan cerminan dari kegagalan struktural dalam menyediakan ruang yang layak bagi warganya. Di tengah himpitan ekonomi, kebijakan yang masih homogen, dan minimnya intervensi jangka panjang, muncul realitas bahwa jalanan menjadi tempat untuk mengadu nasib. Kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terarah dengan menciptakan program pemberdayaan berbasis kebutuhan nyata para pengamen. Dengan demikian, Yogyakarta tidak hanya mempertahankan identitasnya sebagai kota budaya dan pendidikan, tetapi juga memperkuat perannya sebagai ruang hidup yang inklusif dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Referensi
Pandangan Jogja. (2023, Agustus 15). Satpol PP DIY Larang Pengamen di Perempatan Meski Pakai Sound System Bagus. Kumparan. https://kumparan.com/pandangan-jogja/satpol-pp-diy-larang-pengamen-di-perempatan-meski-pakai-sound-system-bagus-20zneygIsEi/full