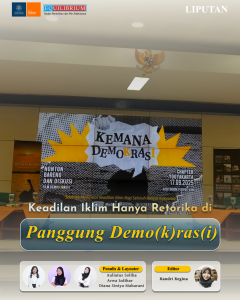Penulis: Atha Bintang Wahyu Mawardi, Dwi Zhafirah Meiliani, Devita Ajeng Kristanti / EQ
Editor: Nawfal Aulia / EQ
Layouter: Arasty Lyla Ramadhani / EQ
Pada 20 Maret 2025 malam hari hingga keesokan dini hari, ratusan (mungkin hingga ribuan) mahasiswa dan anggota masyarakat sipil berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Yogyakarta, untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi yang diprakarsai oleh aliansi masyarakat sipil dan sejumlah kelompok masyarakat ini menyoroti dua isu utama: Revisi pasal dalam UU TNI 2004, dan persoalan transparansi serta komunikasi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan.
Revisi UU TNI, yang kini tengah ramai diperbincangkan, dinilai berpotensi mengurangi ruang bagi supremasi sipil, dengan memberikan lebih banyak ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil. Beberapa pasal yang diubah, seperti penambahan lembaga yang melibatkan militer dipandang sebagai langkah mundur menuju dwifungsi ABRI—di mana militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga mengintervensi bidang-bidang lain yang lebih bersifat sipil. Hal ini, menurut sebagian kalangan, dapat mengancam keberlangsungan sistem demokrasi yang seharusnya memisahkan antara ranah sipil dan militer.
Entah betul atau tidak kekhawatiran satu pihak atau optimisme pihak yang lain, dari sudut pandang yang lebih terbuka, penting untuk kita memahami bahwa setiap kebijakan atau perubahan undang-undang tentu tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Proses revisi ini bisa dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan UU TNI dengan kebutuhan perkembangan zaman, terutama terkait dengan dinamika geopolitik dan kebutuhan pertahanan negara yang semakin kompleks. Tentu saja, argumen yang diajukan oleh para pendukung revisi UU ini menganggap bahwa TNI perlu mendapatkan kewenangan yang lebih besar di beberapa sektor untuk memastikan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, para pendukung berargumen bahwa revisi yang dibuat ini sejatinya tidak bermasalah dan malah memberi garis lebih kuat untuk batas kerja seorang anggota TNI. Sebagai contoh, beberapa mendukung pengesahan draft pasal pada ter-revisi 47 ayat 2 yang menyatakan bahwa, dan kami kutip, “Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengajukan keberatan yang sangat tajam terkait perubahan tersebut yang mana menurut mereka, setiap langkah yang memungkinkan TNI masuk lebih jauh ke dalam ranah sipil akan mengurangi independensi lembaga-lembaga sipil yang selama ini berfungsi untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka khawatir bahwa peningkatan peran TNI dalam sektor sipil akan mengubah cara kerja yang seharusnya mengedepankan kebebasan berpendapat, dialog, dan kritik—sebuah prinsip yang menjadi fondasi sistem demokrasi yang sehat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kebebasan sipil masih bisa terjamin jika kekuasaan militer semakin meluas?
Namun terlepas itu semua, isu transparansi dalam proses pembuatan kebijakan ini juga menjadi sorotan karena sejumlah narasumber yang terlibat dalam aksi 20-21 Maret 2025 tersebut mengungkapkan ketidakjelasan terkait draft RUU TNI yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka menyatakan bahwa seringkali draft yang beredar berbeda dengan yang disahkan oleh DPR. Ketidakterbukaan ini memunculkan perasaan di kalangan masyarakat bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam proses yang seharusnya melibatkan banyak pihak untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif.
Salah satu narasumber mengatakan, “Kami sebagai masyarakat sipil tidak pernah diberikan draft RUU ini secara terbuka. Informasi yang kami terima ternyata berbeda dengan yang disahkan di DPR.” Ketidakjelasan ini kemudian memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap niat pemerintah dalam menyusun kebijakan yang seharusnya bersifat inklusif dan transparan.
Di sisi lain, meskipun pemerintah sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi, misalnya melalui diskusi tertutup seperti yang terjadi di Hotel Fairmont, ada kesan bahwa pendekatan ini cenderung terburu-buru dan dilakukan dengan cara yang tidak melibatkan secara aktif berbagai elemen masyarakat. Ini memperlihatkan adanya celah dalam komunikasi antara pemerintah dan publik, yang bisa saja berdampak pada munculnya ketegangan dan kekhawatiran masyarakat sipil.
Sebuah pandang lain
Revisi ini, dalam pandangan sebagian kalangan, mungkin merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pertahanan yang lebih tangguh. Mengingat situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, pemerintah mungkin berupaya memastikan bahwa TNI memiliki cukup ruang untuk bertindak dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara.
Di sisi lain, jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat sipil, kekhawatiran terhadap meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan dominasi militer dalam politik yang berujung pada Orde Baru. Oleh karena itu, adanya kesadaran kritis dalam masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, di mana setiap perubahan besar harus selalu dipertanyakan dan dibahas secara terbuka.
Tantangan terbesar dalam situasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narasumber dalam wawancara, adalah masalah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Seandainya pemerintah lebih proaktif dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan mendalam mengenai revisi ini sejak awal, mungkin banyak kesalahpahaman dan ketegangan yang bisa dihindari. “Jika pemerintah lebih transparan, mungkin aksi ini bisa dihindari,” ujar seorang demonstran yang terlibat dalam aksi tersebut.
Menilai kembali masalah komunikasi yang buruk ini, munculnya aksi seperti ini dapat dilihat sebagai refleksi dari ketidakpuasan yang lebih besar terhadap cara pemerintah mengelola kebijakan publik. Ketiadaan ruang untuk dialog yang lebih luas, serta sikap yang menurut pihak demonstran terkesan terburu-buru dan eksklusif dalam pengambilan keputusan, bisa memperburuk situasi dan memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakpercayaan yang terus berkembang hanya akan memperburuk keadaan, dan pada akhirnya memperburuk iklim demokrasi di Indonesia.