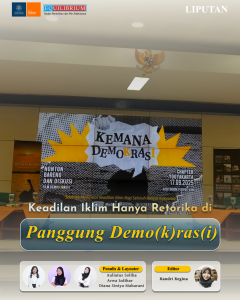Penulis: Atha Bintang Wahyu Mawardi
Editor: Hilda Bhakti
Indonesia saat ini menghadapi fenomena unik: masyarakat dengan akses luas terhadap informasi dan pendidikan, tetapi mengalami kemunduran dalam kebebasan intelektual. Fenomena ini disebut “pintar-pintar bodoh,” di mana pengetahuan digunakan bukan untuk memperkaya dialog, tetapi mempertahankan pandangan yang kaku. Ironisnya, di era digital, masyarakat yang seharusnya lebih terbuka justru semakin tertutup oleh sikap otoriter, baik dari negara maupun individu.
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat sejarah otoritarianisme di Indonesia yang berawal dari era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah membungkam perbedaan pendapat dengan alasan keamanan nasional. Pada masa ini, Pancasila digunakan untuk mewajibkan keseragaman ideologi, dan kritik dipandang sebagai ancaman. Pembungkaman ini menanamkan rasa takut akan perbedaan ideologi dalam jiwa bangsa Indonesia. Kemudian, setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berusaha memulihkan pluralisme dan kebebasan berpendapat. Gus Dur membuka ruang bagi kebebasan berideologi, beragama, dan berekspresi, meskipun masa kepresidenannya yang singkat membuat upaya reformasi ini rentan.
Di era pasca 2000-an, masyarakat Indonesia semakin terhubung melalui media sosial, ruang baru untuk menyuarakan pendapat. Namun, media sosial melahirkan fenomena “otoritarianisme pribadi,” di mana individu memaksakan pandangan mereka dan menolak perbedaan pendapat. Alih-alih menjadi medium dialog, media sosial sering menjadi ajang membungkam orang lain, menciptakan semacam “polisi kebenaran” yang menegakkan pendapatnya sebagai mutlak benar. Hal ini berbahaya, karena masyarakat semakin terkotak-kotak oleh pandangan yang kaku.
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), wajah baru otoritarianisme muncul, disebut sebagai “otoritarianisme lunak.” Jokowi dikenal sebagai sosok pro-rakyat, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Namun, pemerintahannya sering menggunakan hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama di media sosial. Hukum pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sering diterapkan terhadap aktivis, jurnalis, atau masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Fenomena ini mengingatkan pada praktik Orde Baru, meski dalam bentuk lebih halus.
Salah satu contoh otoritarianisme lunak ini adalah Omnibus Law, undang-undang untuk menarik investasi asing dengan menyederhanakan regulasi. Undang-undang ini memicu protes dari serikat buruh, aktivis lingkungan, dan masyarakat yang khawatir dampaknya terhadap hak pekerja dan lingkungan. Pemerintah merespon protes ini dengan tindakan tegas, dan banyak aktivis menghadapi konsekuensi hukum. Respon pemerintah ini mencerminkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi ketimbang penghormatan terhadap suara rakyat.
Kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi sering disertai retorika nasionalisme. Pemerintahan Jokowi menggunakan semangat kemandirian nasional untuk memperkuat dukungan publik, yang terkadang berujung pada nasionalisme intoleran. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pengkhianatan bangsa, dan yang berani berbeda pendapat diberi label “tidak nasionalis” atau “agen asing.” Hal ini menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat tidak hanya ditantang, tetapi juga distigmatisasi sebagai ancaman persatuan nasional.
Konservatisme agama juga mempengaruhi kebebasan berekspresi di Indonesia. Meskipun Jokowi memposisikan dirinya sebagai pemimpin sekuler, pemerintah cenderung mengakomodasi kelompok agama konservatif, terutama untuk kepentingan politik. Misalnya, dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Kristen dekat dengan Jokowi, didakwa menista agama. Pemerintah tidak banyak melindungi proses demokratis dari intervensi konservatif, menunjukkan ambivalensi terhadap pluralisme. Hal ini menimbulkan kesan bahwa toleransi beragama dan kebebasan berekspresi sering dikorbankan demi stabilitas politik.
Peraturan penistaan agama menjadi contoh bagaimana kelompok konservatif memanfaatkan hukum untuk mengekang kebebasan berpendapat. Dalam banyak kasus, peraturan ini diterapkan untuk membungkam kritik yang tidak sejalan dengan interpretasi agama tertentu. Kelompok radikal sering menggunakan retorika “kembali ke kemurnian” sebagai penangkal terhadap ancaman moral. Dalam iklim ini, kebebasan berbicara terbatas oleh negara dan tekanan sosial dari kelompok-kelompok tertentu. Radikalisme agama menjadi ancaman nyata bagi pluralisme yang diupayakan oleh tokoh seperti Gus Dur.
Situasi ini diperburuk oleh kebangkitan nasionalisme religius, di mana identitas agama dijadikan tolok ukur “ke-Indonesia-an.” Kaum ini berpendapat bahwa menjadi “Indonesia sejati” adalah dengan mengikuti interpretasi agama mereka. Nasionalisme ini, ketika digabungkan dengan konservatisme agama, menciptakan visi Indonesia yang sempit dan intoleran terhadap perbedaan ideologi. Kritik yang bertentangan dengan pandangan agama atau nasionalisme versi mereka seringkali dianggap sebagai tindakan anti-nasional.
Pada akhirnya, otoritarianisme yang melibatkan individu, kelompok sosial, dan negara menciptakan masyarakat yang cenderung membungkam daripada mendukung dialog. Alat-alat berpikir kritis digunakan bukan untuk mempertanyakan, tetapi untuk memperkuat pandangan yang sudah ada. Masyarakat yang seharusnya kaya perspektif justru terbatas oleh ketakutan untuk berbeda pendapat. Hasilnya adalah iklim di mana kecerdasan tidak digunakan untuk membuka diri, tetapi memperkuat sekat-sekat ideologi yang membatasi pemahaman kolektif.
Indonesia perlu merefleksikan kondisi ini. Jika kita mempertahankan pandangan kaku dan menutup ruang dialog, bangsa ini berisiko stagnan secara intelektual dan tertinggal dalam persaingan global. Demokrasi sejati membutuhkan keberanian untuk mendengar dan menghargai perbedaan, bukan mempertahankan ide-ide yang dianggap aman. Hanya dengan membebaskan diri dari otoritarianisme, baik dari negara maupun masyarakat, Indonesia dapat mencapai potensinya sebagai bangsa yang plural dan demokratis.